,_op_N.V._Cultuur_Maatschappij_Ophir_op_Sumatra_'s_Westkust,_KITLV_184570.tiff.jpg) |
| Sumber Gambar KITLV A1427 |
Kitab Ahla al Musamarah fi Hikayat al Auliya al ‘Asyrah karangan Syekh Abu Fadhol memberikan narasi yang cukup panjang tentang Sunan Ngudung. Sunan Ngudung dikisahkan memiliki peran signifikan dalam peperangan antara kerajaan Demak melawan Majapahit. Pada laporan Babad kerajaan Banten, terjadi konfrontasi antara Demak dengan Majapahit terjadi beberapa tahun. Dua kekuatan yang berhadap-hadapan antara barisan Islam yaitu para ulama dari Kudus, imam masjid Demak di bawah pimpinan Pangeran Ngudung melawan Majapahit yang berafiliasi dengan pasukan dari Klungkung, Pengging dan Terung.
Rekonstruksi peperangan antara Demak dan Majapahit yang dibuat oleh beberapa penulis buku sejarah seakan membenarkan bahwa Ngudung yang memiliki nama asli Utsman Haji lebih dikenal sebagai panglima perang handal pada jamannya. Narasi literer atau referensial berbanding lurus dengan pitutur lisan beberapa informan penelitian ini. Juru kunci makam Sunan Ngudung mengisahkan bahwa Desa Wadung, tempat makam Sunan Ngudung merupakan tempat “persidangan para wali dan pasukan perang” dari kerajaan Demak. Tim peneliti jejak waliyullah penyebar Islam di Tuban Bumi Wali, sempat ditunjukkan goa pertemuan tempat sidang para wali khususnya ketika menyusun strategi perang. Masih banyak cerita warga Desa Wadung seputar bagaimana desa ini memiliki peran dan dijadikan tempat pasukan Demak ketika menghadapi perang melawan Majapahit. Hanya saja selain bekas tempat para wali bersidang, artifak yang mendukung pernyataan warga tidak bisa ditemukan.
Selain sebagai panglima perang seperti tergambarkan di atas, Sunan Ngudung memiliki jejak historis sebagai penyebar Islam di wilayah Tuban khususnya di Desa Wadung Kecamatan Soko. Agus Sunyoto menegaskan jejak dakwah Sunan Ngudung adalah pencipta tari jaranan atau jatilan. Tari jaranan digunakan sebagai media dakwah keliling untuk mengumpulkan warga di lapangan desa. Setelah berkumpul kemudian warga diajak untuk membaca kalimat syahadat. Ruh al Dakwah adaptif akulturalif Sunan Ngudung menginspirasi penyebar Islam setelah beliau, sekurang-kurangnya tercermin dalam amaliyah dakwah putranya yaitu Sunan Kudus.
Melacak Geneologi Sunan Ngudung
Raden Utsman Haji memiliki hubungan kekerabatan atau nasab dengan waliyullah lainnya. Utsman Haji adalah putra dari Raden Raja Pandito saudara Raden Rahmat (Sunan Ampel) dan Siti Zaenab. Utsman Haji, Raden Rahmat dan Siti Zaenab adalah putra-putri dari Ibrahim al Asmar. Bagan di bawah diharapkan bisa berbicara lebih jelas tentang garis keturunan Sunan Ngudung.
Ibrahim-Al Asmar Bin Jamadul Kubro/Najmuddin Kubro Dan Condrowulan Binti Raja Campa memiliki tiga orang anak Raden Raja Pendito, Raden Rahmat (Sunan Ampel) dan Sayidah\nZaenab. Kemudian Raden\nRaja Pendito memiliki tiga keturunan. Haji Utsman yang menikah dengan Sayidah Syarifah Binti\nRaden Rahmat (Sunan Ampel), Utsman Haji yang menikah dengan Dewi\nSri Binti Raden Syukur Bin Arya Tejo Bin Arya Galuh, dan Ayu Gedhe Tundha. Utsman Haji yang menikah dengan Dewi\nSri Binti Raden Syukur Bin Arya Tejo Bin Arya Galuh memiliki dua anak yakni Sujinah serta Amir\nHaji (Sunan Kudus) yang menikah dengan Sayidah Rahil Binti Sunan Bonang.
Garis keturunan Sunan Ngudung apabila ditarik ke atas, maka akan muttashil hingga ke Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidah Fatimah al Zahra berputra Zainul Abidin berputra Zainul Hakam berputra Zainul Husain berputra al Zain al Kabir berputra Najmudin al Kabir berputra Najmudin al Kabir berputra Syam’un berputra Ustar berputra Abdullah berputra Abdurrahman berputra Mahmud Akbar berputra Najmuddin Akbar kemudian berputra Ibrahim al Asmar. Ibrahim al Asmar menikah dengan Condrowulan putri Raja Campa. Perkawinan ini menghasilkan tiga putra, salah seorang di antaranya adalah Raden Pandito. Raden Raja Pandito menikah dengan Maduretno binti Arya Briben bin Arya Galuh bin Rondo Kuning bin Arya Mentaun bin Arya Banjaran bin Munding Wangi. Pasangan Suami Isteri, Raja Pandito dan Maduretno ini memiliki tiga anak, salah satunya adalah bernama Utsman Haji yang lebih dikenal dengan Sunan Ngudung.
Berdakkwah dengan Tari Jaranan
Konstribusi terpenting dari Sunan Ngudung adalah ikut meletakkan pondasi moderasi dakwah dengan memanfaatkan tarian jaranan. Ada dua pendapat yang menyebutkan tentang asal usul dan tahun kemunculan kesenian jaranan. Pertama, kesenian jaranan mulai muncul sejak abad ke X atau sekitar tahun 1041 bersamaan dengan kerajaan Kahuripan terbagi dua, yaitu bagian timur kerajaan Jenggala dengan ibukota Kahuripan dan sebelah barat kerajaan Panjalu (Kediri) beribukota Dhahapura.
Kedua, kesenian jaranan sudah tumbuh dan berkembang sekitar abad 14 – 15 M. Sejarahnya dapat ditracing dari catatan Agus Sunyoto (2012) yang menyebutkan bahwa kesenian ini lahir pada masa transisi jaman Hindu ke Islam. Pada saat itu, kesenian ini oleh para wali dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Wali yang pertama kali mengajarkan dan menggelar kesenian jaranan adalah Sunan Ngudung.
Dikisahkan bahwa kesenian jaranan merupakan penggambaran dari kisah perjuangan Raden Fatah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Substansi nilai yang disuguhkan dalam kesenian ini selain mengandng nilai-nilai estetika, juga nilai-nilai kebaikan (ma’ruf) dan mencegah kebathilan (munkar). Kebaikan dan kemunkaran merupakan nilai yang melekat (tabiati) dalam keseluruhan dimensi kemanusiaan sebagai insan beragama. Jaranan juga mengandung nilai yang memotivasi manusia agar memiliki etos kerja tinggi dalam menghadapi kompetisi hidup yang keras. Literatur lain menyebutkan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono I kesenian jaranan dikisahkan sebagai tarian perang pasukan Mataram dalam menghadapi pasukan Belanda. Kesenian jaranan disebutkan juga dikembangkan oleh sisa-sisa prajurit Pangeran Diponegoro untuk menyatukan rakyat pribumi melawan penjajah.
Keterkaitan antara kesenian dan dakwah paralel dengan dua sisi mata uang koin yang saling melengkapi. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan memiliki kesamaan misi yaitu sebagai perantara pesan kepada seseorang atau kelompok. Islam merupakan mata air bagi kesenian dan sebaliknya kesenian digunakan untuk ketinggian syiarnya agama. Islam tidak mengenal konsep dan paham “seni untuk seni”, tetapi seni untuk akhlak al karimah. Pada masa transisi dari Hindu ke Islam pada abad 14 – 15 masyarakat Jawa telah memiliki kesenian dan kebudayaan yang mengakar. Sejumlah kesenian dan kebudayaan itu kemudian dimodifikasi untuk keperluan syiar Islam dengan tanpa mengubah substansi nilai di dalamnya, sebagaimana kesenian wayang kulit.
Terpisah dari adanya silang pendapat mengenai asal-usul dan tahun kemunculan tari jaranan, fakta sejarah (sebagai diungkap oleh Agus Sunyoto) menunjukkan tari jaranan pernah dijadikan Sunan Ngudung sebagai media dakwah pada masa pemerintahan Raden Fatah. Bathoro Katong, Raja Islam Ponorogo, juga menggunakan kesenian jaranan yang telah dimodifikasi menjadi reog untuk kepentingan dakwah Islam.
Sejumlah atraksi yang ditampilkan melalui lambang dan simbol dalam tari jaranan berkaitan dengan watak dasar manusia. Simbol tersebut kemudian divisualisasikan secara estetis antara kemunkaran, kebenaran, keindahan dan ketuhanan. Unsur dakwah dalam tari jaranan tergambar mulai unsur tari sembahan, instrumen, tembang busana dan tokoh. Unsur gamelan menggambarkan makna moralitas yang ditransmisikan melalui bunyi alat musik mengajak kontemplasi pendengarnya agar selamat di dunia dan akhirat. Unsur tembang memaknakan dan menggambarkan pesan keagamaan agar dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia. Unsur busana yang disebut dengan “iket” merefleksikan anjuran untuk menutup aurat. Tokoh tari jaranan digambarkan dalam simbol kuda yang ditunggangi manusia agar berjalan lurus sesuai nilai-nilai Islam di tengah berbagai macam godaan untuk berbuat kemunkaran. Simbol kemunkaran dalam tari jaranan digambarkan dengan barongan dan celeng.
Akhirnya dari rekonstruksi sejarah yang dibuat oleh para sejarawan, memperlihatkan bahwa kreativitas Sunan Ngudung menciptakan tari jaranan sebagai fakta bahwa dakwah mampu bersanding dengan tradisi, kebudayaan, dan bahkan keyakinan lain. Ada ungkapan bijak: “kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar pula”. Di antara cara menyampaikan kebenaran itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, menjamu bukan menggurui, dan mengajarkan dengan keramahan bukan kemarahan.
Kesenian Jathilan yang di beberapa daerah disebut Seni Kuda Lumping atau Kuda Kepang dikenal sebagai kesenian tradisional di yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian menghubungkan kesenian ini berasal dari cerita Panji, sebagian yang lain menghubungkannya dengan perlawanan gerilya Pangeran Diponegoro. Ada pula sumber yang menyatakan bahwa kesenian jathilan ini asalnya dari jawa timur, tepatnya kesenian Reog Ponorogo.dikatakan sebagai pemain Jothil. Namun cerita tertua menyebutkan bahwa kesenian ini yang memperkenalkan kali pertama adalah Sunan Ngudung, ayah Sunan Kudus, yang menggelar pertunjukan jathilan untuk mengumpulkan masyarakat guna didakwahi agama Islam.
Saat ini, kesenian Jathilan hidup dan berkembang luas terutama di Jawa Tengah terutama di sepanjang bukit Menoreh, Salam, Borobudur, Salaman, Muntilan, Kajoran, Kaliangkrik. Bagi masyarakat di sekitar bukit Menoreh kesenian Jathilan merupakan salah satu jenis kesenian rakyat yang berkembang di daerah pegunungan menoreh, tepatnya di sebelah selatan candi Borobudur. Kesenian ini memiliki latar belakang yang berhubungan dengan sejarah perang gerilya Pangeran Diponegoro. Menurut cerita, penduduk terinspirasi saat melihat pasukan Pangeran Diponegoro yang sedang melakukan perang gerilya di sepanjang pegunungan Menoreh. Seringnya masyarakat sekitar pegunungan Menoreh melihat dan menyaksikan pasukan gerilya Pangeran.Diponegoro membuat mereka terinspirasi untuk mengekspresikan inspirasinya itu dalam bentuk kesenian yang diiringi musik gamelan yang diwujudkan dengan penari yang menaiki kuda yang terbuat dari kepang/anyaman bambu. Maka kesenian jathilan ini kadang juga dinamakan dengan kesenian kuda Kepang/kuda Lumping.
Yang lazim dari Kesenian Jathilan ini adalah digunakannya media trance untuk berhubungan dengan kekuatan gaib yang diyakini sebagai sesepuh desa mereka. Ada beberapa desa masih memiliki keyakinan akan hal tersebut. Salah satu contoh yang sampai saat ini masih mereka lakukan adalah, setiap mereka melakukan pementasan mereka harus membawa air dari mata air di mana terdapat batu bekas telapak kuda, yang dipercaya sebagai bekas telapak kaki kuda Pangeran Diponegoro. Tradisi ini masih mereka bawa hingga sekarang dan hal ini sudah menjadi tradisi mereka dalam menggelar kesenian jathilan ini di setiap pertunjukan.
Trance dalam pertunjukan jathilan juga kadang dipergunakan untuk menolak bala/ tolak bala atau menyembuhkan penyakit bagi orang yang mempercayainya. Kekuatan alam ini sampai sekarang kadang masih mereka lakukan dalam setiap hajatan. Masyarakat mereka yang memiliki kaul/ kehendak untuk menggunakan kesenian ini untuk merayakan sebuah perayaan, baik khitanan, perkawinan bahkan nadar dari seseorang yang memang menghendakinya. Setiap kelompok kesenian jathilan selalu memiliki seorang dukun yang dianggap sebagai sesepuh di kelompok tersebut yang menjadi Penetralisasi Trance. Sang dukun ini menjadi sebuah mediator yang menjembatani antara manusia dan roh kekuatan magis tersebut.
Selain Penari Prajurit, biasanya dalam pertunjukannya mereka juga menggunakan beberapa topeng Buto yang menjadi pelengkap dari keseluruhan pertunjukan kesenian jathilan tersebut yang disebut Grasak. Bagian pertunjukan grasak ini biasanya merupakan babak terakhir dari keseluruhan rangkaian pertunjukan kesenian jathilan.[]
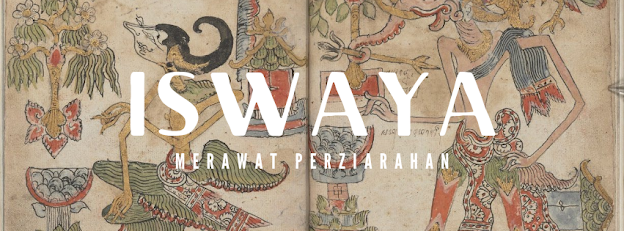
Komentar
Posting Komentar