Iswaya.my.id - Kepentingan, betapapun sederhana kedengarannya, tak pernah hadir dengan wajah tunggal. Ia selalu terdiri dari lapisan-lapisan yang saling bersilang: ada yang mendesak, ada yang hanya mungkin berjalan bila syarat tertentu terpenuhi, dan ada yang terpaksa ditunda karena kondisi yang menghalangi untuk mewujudkannya.
Nyatanya, tidak sedikit yang kerap gagal membedakan mana yang seharusnya menjadi prioritas dan mana yang baru bisa tumbuh dalam kondisi yang tepat.
Dalam kehidupan sosial, kebingungan itu sering melahirkan ketidakadilan. Hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas bersama justru tercecer, digantikan oleh kepentingan sesaat. Sementara kepentingan yang memerlukan kondisi matang dipaksakan berjalan, meski di sekelilingnyalah yang menanggung akibatnya.
Dari situ lahirlah jurang, antara kebutuhan sejati manusia dan agenda sempit kekuasaan.
Ambil contoh dunia kebudayaan. Kita sering mendengar semboyan pelestarian, tetapi pelestarian hanya tinggal slogan. Kesenian tradisi, misalnya, disanjung di panggung festival, diiklankan di brosur pariwisata, namun ditinggalkan di kampung halaman.
Kepentingan budaya ditempatkan sebagai prioritas seremonial, padahal dalam kondisi nyata, ia justru kekurangan dukungan.
 |
| Sumber Gambar; Markey.id |
Begitu juga dengan solidaritas sosial. Betapa mudah kita tergugah saat bencana melanda. Sumbangan mengalir deras, aksi sosial berderet di jalan. Namun tatkala bencana reda, kepentingan itu menguap.
Sisanya adalah kenangan singkat, muspro. Pada kondisi ini, menegaskan bahwa kesadaran kemanusiaan ternyata masih berdiri di ruang kondisional, hadir bila ada kejutan, hilang kemudian dan menjadi biasa-biasa saja.
Kita mesti jujur mengakui, kepentingan kerap terbelenggu oleh persepsi sepihak, bahkan segelintir kecongkahan-kecongkahan. Mereka yang memegang kendali politik atau ekonomi sering mengklaim sebagai penentu akan apa yang penting, apa yang tidak.
Masyarakat luas akhirnya hanya menjadi followers yang - bahkan menjadi pengikut setia dan buta, sehingga menerima tafsir yang sudah ditentukan. Padahal, kepentingan sejati tak pernah lahir dari satu arah. Ia mesti menjadi hasil dari percakapan panjang. Kira-kira ya seperti penempaan para empu terhadap sebilah keris, dari lipatan 2000 sampai 8000 lipatan deng panas api yang berlipat-lipat suhunya, akan melahirkan keris yang indah dengan berbagai pamornya.
Dalam ruang kebudayaan, tafsir sepihak itu sangat kentara. Sebuah tarian bisa dianggap “tak produktif” lalu dihapus dari ruang sekolah, sementara kurikulum dipadatkan dengan keterampilan yang disebut “berguna”. Pertanyaannya berguna bagi siapa? Apakah kegunaan hanya diukur dari angka ekonomi, bukan dari makna kehidupan bersama?
Kita sedang berada di zaman yang begitu cepat berubah. Teknologi, ekonomi, dan politik terus bergerak. Namun justru karena itu, ruang prioritas harus ditata lebih hati-hati. Jika tidak, kita akan mengorbankan hal-hal mendasar—seperti identitas, nilai kebersamaan, atau bahkan rasa percaya—demi kecepatan yang semu.
Kesadaran sosial juga harus ditempatkan di situ. Kemanusiaan tidak boleh menunggu kondisi darurat untuk menjadi penting. Ia mesti hadir sebagai prioritas abadi. Setiap kebijakan, setiap proyek pembangunan, seharusnya selalu ditimbang dari dampaknya terhadap manusia yang paling rentan.
Sayangnya, cara kita menimbang kepentingan masih terjebak dalam logika utilitas sepihak. Percaya atau tidak, yang dihitung hanya apa yang bisa memberi keuntungan cepat. Akibatnya, kepentingan budaya dan kemanusiaan sering menjadi korban. Mereka dianggap mewah, tambahan, bahkan sekedar pelengkap, atau jangkep-jangkepan.
Padahal, bila kita telisik, kepentingan budaya dan kemanusiaan bukanlah ornamen. Mereka justru menjadi fondasi yang menopang keberlangsungan masyarakat. Tanpa budaya yang hidup, kita kehilangan arah. Tanpa kemanusiaan yang hadir, kita kehilangan makna.
Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana menata ulang cara kita melihat kepentingan? Bagaimana agar prioritas tak hanya ditentukan oleh yang kuat, dan kondisi tak hanya menjadi alasan untuk menunda yang penting?
Mungkin kita perlu belajar menimbang dari sudut yang lebih luas: bukan sekadar dari hitungan praktis, melainkan dari kesadaran bahwa masyarakat adalah rumah bersama. Kepentingan satu pihak yang meminggirkan yang lain, cepat atau lambat, akan menghancurkan rumah itu sendiri.
Dalam konteks kebudayaan, ini berarti memberi ruang hidup bagi tradisi tanpa harus memaksa ia membeku. Biarkan tradisi bernapas, beradaptasi, sekaligus tetap dihormati. Prioritasnya bukan sekadar mempertahankan bentuk, tetapi menumbuhkan makna. Kondisinya harus diupayakan: pendidikan, dukungan ekonomi, dan ruang kreatif bagi generasi muda.
Dalam konteks sosial-kemanusiaan, ini berarti menata solidaritas agar tidak berhenti di bencana. Kita perlu menjadikan kepedulian sebagai kebiasaan sehari-hari dalam kebijakan, dalam kerja-kerja komunitas, bahkan dalam perilaku sederhana antarwarga. Prioritasnya bukan hanya menolong di kala darurat, tapi membangun sistem yang adil sebelum darurat datang.
Ada pula soal siapa yang bicara. Suara mayoritas sering dianggap mewakili semua orang. Tetapi realitas menunjukkan, minoritas kerap menanggung beban paling berat. Maka, dalam menata kepentingan, hak-hak minoritas mesti diposisikan sejajar. Keadilan sosial hanya lahir bila suara yang kecil pun dihitung sebagai prioritas.
Di sinilah kita melihat bahwa prioritas tidak bisa diputuskan sepihak. Ia harus menjadi hasil musyawarah yang sungguh-sungguh. Bukan musyawarah formal yang sekadar meresmikan keputusan yang sudah jadi, melainkan musyawarah yang membuka ruang dengar—di mana suara yang biasanya tenggelam diberi tempat.
Musyawarah semacam ini bukan hanya persoalan prosedur. Ia mencerminkan kesadaran bahwa kepentingan adalah urusan kolektif. Dan bila kolektif, maka tidak boleh ada yang merasa dirugikan demi yang lain. Prioritas dan kondisi mesti dilihat sebagai keseimbangan bersama.
Dari sini lahir tawaran solusi. Pertama, kita perlu membangun sistem yang menempatkan kebudayaan dan kemanusiaan sebagai syarat utama dalam setiap agenda pembangunan. Jika pembangunan ekonomi ingin berjalan, syaratnya adalah tidak merusak budaya dan tidak menyingkirkan manusia.
Kedua, kita perlu menumbuhkan mekanisme partisipasi yang nyata. Masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan apa yang penting bagi mereka, bukan hanya diberi paket keputusan. Partisipasi ini bisa lewat forum lokal, lembaga budaya, atau komunitas warga yang punya hak bicara setara.
Ketiga, kita perlu mengubah cara pandang terhadap kondisi. Kondisi tidak boleh selalu dipakai sebagai alasan untuk menunda. Justru kondisi harus diupayakan, jika pelestarian budaya memerlukan dukungan ekonomi, maka dukungan itu harus dirancang. Jika solidaritas sosial memerlukan sistem perlindungan, maka sistem itu harus dibangun.
Dengan cara ini, kepentingan tidak lagi menjadi alasan yang timpang. Ia benar-benar menjadi ruang bersama, di mana prioritas dan kondisi saling menopang, bukan saling menghalangi.
Tentu, perjalanan ini tidak mudah. Akan ada tarik menarik kepentingan, ada resistensi, ada godaan untuk kembali pada cara lama. Tetapi tanpa keberanian memulai, kita hanya akan terus terjebak dalam lingkaran seremonial yang hampa.
Pada akhirnya, yang kita butuhkan adalah keseimbangan. Keseimbangan antara warisan budaya dan inovasi modern, antara kebutuhan mendesak dan kesiapan jangka panjang, antara suara mayoritas dan hak minoritas.
Kesadaran semacam itu tidak bisa dibentuk oleh aturan saja. Ia harus lahir dari pendidikan, dari kebiasaan, dari pengalaman kolektif. Sekolah, media, dan komunitas punya peran penting menumbuhkan rasa bahwa kemaslahatan bersama selalu lebih tinggi dari keuntungan sesaat.
Kita perlu menegaskan, kepentingan sejati bukanlah milik satu pihak. Ia adalah hak semua. Bila satu pihak dipaksa mengalah terus-menerus, maka kepentingan itu berubah menjadi beban. Sedangkan kepentingan yang adil justru melahirkan kelegaan, semua merasa terlibat, semua merasa memiliki.
Itulah sebabnya, solusi paling mendasar terletak pada keadilan. Keadilan bukan sekadar slogan, tapi cara kerja. Setiap prioritas harus ditimbang dengan pertanyaan sederhana: adakah yang dirugikan? Bila ada, maka keputusan itu harus ditinjau ulang.
Bayangkan sebuah masyarakat yang berani menata kepentingan dengan cara ini. Tradisi tak lagi hanya jadi tontonan, melainkan bagian dari kehidupan. Solidaritas tak lagi bergantung pada bencana, melainkan hadir dalam keseharian. Pembangunan tak lagi berarti merusak, melainkan menumbuhkan.
Masyarakat semacam ini mungkin terdengar utopis. Tetapi justru utopia yang membuat kita bergerak. Utopia bukan janji yang harus tuntas, melainkan arah yang memberi makna. Tanpa arah, kita akan berjalan tanpa tujuan, sibuk dalam kepentingan kecil, lupa pada rumah besar bernama kemaslahatan bersama.
Bahwa kepentingan selalu ada di persimpangan. Apakah ia akan menjadi alat dominasi, atau menjadi ruang kebersamaan, tergantung bagaimana kita menatanya. Dan pilihan itu, pada akhirnya, ada di tangan kita semua.[]
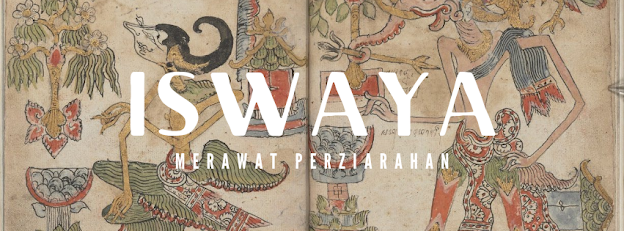
Komentar
Posting Komentar