 |
| Ilustrasi penangkapan Pangeran Diponegoro pada akhir perang Jawa tahun 1830 yang dilukis oleh Raden Shaleh. Foto: Ist/Net |
Iswaya.my.id - Pangeran Diponegoro merupakan salah satu figur paling penting dalam sejarah nasional Indonesia, yang keberaniannya dalam memimpin Perang Jawa (1825–1830) melawan kolonialisme Belanda telah mengukir jejak mendalam dalam kesadaran kolektif bangsa. Namun, keistimewaan Diponegoro tidak berhenti pada perannya sebagai tokoh militer. Ia adalah pemimpin spiritual, intelektual, sekaligus simbol moral yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, budaya Jawa, dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam dirinya, terdapat perpaduan antara idealisme religius dan realisme politik yang lahir dari pergulatan spiritual dan sosial yang kompleks.
Karya Babad yang ditulis oleh Diponegoro dalam pengasingannya (1831–1833) merupakan sumber penting untuk memahami kepribadian dan pandangan dunianya. Babad ini tidak hanya mencatat kronologi peristiwa, tetapi juga mengungkapkan dimensi moral, kosmologis, dan sufistik perjuangan. Melalui gaya bahasa simbolik khas Jawa, teks ini menempatkan perlawanan Diponegoro dalam kerangka spiritual yang lebih luas — sebagai jihad melawan kezaliman dan ketidakseimbangan kosmos.
Membaca dan menelaah representasi Pangeran Diponegoro menjadi salah satu upaya laku; bahwa Babad Diponegoro bukan hanya semata teks historiografis, tetapi juga teks "spiritualitas" ( dalam kerangkan suluk sosial kemanusiaan) yang menggambarkan perjuangan manusia melawan kolonialisme eksternal dan kolonialisme batin.
Kajian tentang Pangeran Diponegoro telah menghasilkan banyak interpretasi yang melampaui batas disiplin sejarah. Peter Carey (2017) dalam Takdir; Riwayat Pangeran Diponegoro menyajikan biografi intelektual dan spiritual tokoh ini dengan mengungkapkan keterkaitannya dengan tradisi tasawuf, etika Islam, dan gerakan rakyat. Carey menegaskan bahwa Perang Jawa tidak hanya merupakan perang politik, tetapi juga perang moral untuk menegakkan keadilan ilahi (jihad fi sabilillah).
M. C. Ricklefs (2001) menafsirkan perlawanan Diponegoro sebagai titik peralihan penting dalam sejarah Islam-Jawa, di mana nilai-nilai keagamaan mulai membentuk perlawanan politik melawan kekuasaan kolonial. Menurutnya, Islam menjadi bahasa moral yang mempersatukan rakyat Jawa dalam menghadapi penindasan ekonomi dan sosial yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Sementara Clifford Geertz (1976) menyoroti posisi unik Diponegoro dalam stratifikasi sosial Jawa. Ia menyebut Diponegoro sebagai sosok yang menjembatani kategori "santri" dan "priyayi" seorang bangsawan yang hidup dalam kesederhanaan, menjalani laku spiritual, dan menolak kemewahan istana. Dalam kerangka antropologis Geertz, Diponegoro melambangkan sintesis antara religiusitas Islam dan etika Jawa yang menekankan keseimbangan batin.
Kajian lokal seperti Babad Diponegoro versi Sri Wintala Achmad (2020) menempatkan tokoh ini dalam kesinambungan sejarah panjang sejak Majapahit hingga Mataram. Teks ini menekankan bahwa Diponegoro merupakan pewaris legitimasi spiritual (wahyu keprabon) dan moralitas kepemimpinan Jawa yang bersumber dari ajaran leluhur dan nilai Islam.
Studi kontemporer memperluas pemahaman ini. Ittihadiyah (2024) dalam penelitiannya tentang kehidupan masyarakat Bagelen setelah Perang Jawa menunjukkan bahwa perlawanan Diponegoro meninggalkan warisan sosial dan spiritual yang panjang: masyarakat menciptakan "tatanan baru" yang berupaya memadukan kepatuhan kolonial dengan memori spiritual perjuangan. Sementara Robingun dan Nugroho (2024) mengungkap dimensi pendidikan Islam dalam tahannuts atau latihan spiritual Diponegoro, terutama pertemuannya dengan figur Sunan Kalijaga dalam konteks sufistik. Dengan demikian, literatur kontemporer menyoroti bahwa perjuangan Diponegoro tidak berhenti di medan perang, tetapi berlanjut sebagai proses transmisi nilai moral dan spiritual di tengah perubahan sosial yang cepat.
Konteks Historis dan Sosial-Politik
Pada awal abad ke-19, Kesultanan Yogyakarta menghadapi disintegrasi moral dan tekanan kolonial yang luar biasa. Politik intervensi Belanda melalui divide et impera mengikis otoritas raja dan menumbuhkan ketimpangan sosial. Diponegoro, yang lahir dari lingkungan istana, justru memilih menyingkir dari kemewahan ke kehidupan asketis di Tegalreja. Ia melihat kerusakan moral bangsawan dan penderitaan rakyat sebagai tanda ketidakseimbangan kosmos yang harus diperbaiki.
Menurut Carey (2017), tindakan Diponegoro meninggalkan istana bukanlah sekadar protes politik, melainkan bentuk "hijrah spiritual" sekali lagi spiritual di sini lebih pada pemaknaan proses menuju kesadaran, madep. Ia menjalani kehidupan sederhana, menolak harta dan pangkat, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan konsep zuhud dalam tasawuf. Meninggalkan dunia untuk memperoleh kemurnian jiwa.
Ketika pemerintah kolonial berencana membangun jalan yang melintasi tanah leluhurnya tanpa izin, Diponegoro memandang tindakan itu sebagai penistaan spiritual terhadap warisan nenek moyangnya. Dari titik inilah api perlawanan menyala. Namun sebagaimana dijelaskan Ricklefs (2001), perang ini jauh melampaui persoalan tanah. Ia merupakan simbol perlawanan terhadap hegemoni moral Barat dan dominasi politik kolonial.
Babad Diponegoro menempatkan tokoh utama dalam garis genealogis panjang yang menghubungkannya dengan tokoh-tokoh besar Jawa seperti Ki Ageng Sela, Panembahan Senapati, dan Sultan Agung. Garis ini menegaskan kesinambungan antara spiritualitas dan kekuasaan. Dalam pandangan kosmologis Jawa, kepemimpinan yang sah harus didukung oleh kesucian batin dan restu ilahi (wahyu keprabon).
Diponegoro menyadari bahwa legitimasi kekuasaan tidak dapat diperoleh semata dari darah bangsawan, melainkan dari moralitas dan kesadaran spiritual. Dalam versi Sri Wintala Achmad (2020), Diponegoro digambarkan menjalani tapa brata di gunung dan gua, berzikir, serta menerima ilham melalui mimpi dan tanda-tanda alam. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mempersiapkan strategi militer, tetapi juga menyiapkan dirinya sebagai manusia paripurna yang selaras dengan kehendak Tuhan.
Genealogi dalam babad bukan sekadar silsilah, melainkan peta spiritual yang menegaskan bahwa perjuangan Diponegoro adalah bagian dari perjalanan panjang sejarah moral Jawa: dari Majapahit yang menegakkan keadilan, Mataram yang memadukan Islam dengan politik, hingga Yogyakarta yang harus berjuang melawan kolonialisme.
Integrasi Nilai Sufistik dan Budaya Jawa
Nilai-nilai sufistik menjadi inti dalam Babad Diponegoro. Dalam teks tersebut, terdapat pertemuan antara ajaran Islam dan pandangan hidup Jawa yang menekankan harmoni dan pengendalian diri. Robingun dan Nugroho (2024) menjelaskan bahwa laku tahannuts — meditasi dan pengasingan diri yang dilakukan Diponegoro — berfungsi sebagai pendidikan spiritual. Ia belajar dari tradisi para wali seperti Sunan Kalijaga tentang bagaimana kesunyian dan tafakkur dapat melahirkan kekuatan moral.
Manunggaling kawula Gusti (penyatuan hamba dan Tuhan) diterjemahkan Diponegoro ke dalam praksis politik dan sosial. Ia tidak menempatkan dirinya di atas rakyat, tetapi menjadi bagian dari mereka. Konsep ini mencerminkan ideal sufistik tentang fana' (lenyapnya ego dalam kehendak Tuhan). Dengan menanggalkan ego dan ambisi, Diponegoro menemukan legitimasi moral sebagai pemimpin profetik.
Selain itu, nilai-nilai sufistik juga tampak dalam cara Diponegoro menafsirkan perang. Baginya, perang melawan Belanda bukan semata-mata konflik politik, melainkan bagian dari jihad spiritual. Ia menulis dalam babadnya bahwa "musuh sejati bukanlah orang kafir di luar, tetapi hawa nafsu di dalam diri." Pernyataan ini memperlihatkan bahwa jihad Diponegoro mencakup dimensi batin, yakni perjuangan melawan keserakahan, ketamakan, dan egoisme yang menjadi akar penindasan.
Perang Jawa merupakan manifestasi konkret dari integrasi nilai spiritual dan sosial. Diponegoro memimpin perlawanan dengan menggabungkan strategi militer dan dakwah Islam. Ia membangun jaringan ulama dan pesantren sebagai pusat mobilisasi rakyat. Menurut Carey (2017), inilah pertama kalinya dalam sejarah Jawa modern muncul gerakan yang memadukan kepemimpinan religius dan politik rakyat.
Kajian Ibdalsyah et al. (2025) menunjukkan bahwa dakwah Islam Diponegoro di Selarong mempercepat proses Islamisasi komunitas pedesaan yang sebelumnya masih sinkretik. Hal ini memperkuat argumen bahwa perjuangan Diponegoro memiliki dimensi peradaban, bukan hanya pertempuran. Ia berusaha membangun masyarakat beriman yang adil dan bermoral.
Dalam konteks ini, perjuangan Diponegoro dapat dilihat sebagai "spiritual insurgency" (pemberontakan moral/al-dharb al-hal) terhadap sistem kolonial. Konsep ini mengandung pesan universal; bahwa perubahan sosial sejati harus berakar pada transformasi batin manusia.
Tidak bisa dipungkiri bahwa nilai mistisisme juga mewarnai Babad Diponegoro. Ia sarat dengan simbolisme yang mencerminkan pandangan dunia Jawa-Islam. Simbol “Ratu Adil”, misalnya, merepresentasikan figur mesianistik yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan dunia. Tesis Shofiyulloh (2024) menafsirkan konsep Ratu Adil Diponegoro sebagai visi politik-spiritual untuk membangun tatanan masyarakat Islam yang berbasis keadilan sosial.
Selain itu, hubungan simbolis antara Diponegoro dan Ratu Kidul melambangkan harmoni antara kekuatan maskulin dan feminin dalam kosmos. Dalam tradisi sufistik, kesatuan polaritas ini merefleksikan keseimbangan antara lahir dan batin, dunia dan akhirat.
Artinya Babad Diponegoro tidak sekadar menyampaikan narasi perang, tetapi juga menegaskan pandangan kosmologis bahwa perlawanan manusia terhadap penindasan adalah bagian dari usaha menegakkan keseimbangan semesta.
Pertanyaannya adalah nilai-nilai perjuangan Diponegoro secara praktis akan tetap menjadi sebuah perjalanan yang mewaktu. Relevan dengan kondisi apapun. Selagi ia dalam bentuk perjuangan atas penindasan. Seperti yang dikatakan di atas tadi sebaga al-darb al-hal.
Perjuangan Pangeran Diponegoro tetap relevan bagi Indonesia modern. Dalam masyarakat yang dihadapkan pada krisis moral, korupsi, dan materialisme, nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan yang diwariskannya menjadi teladan abadi.
Ittihadiyah (2024) menyoroti bagaimana masyarakat pasca-Perang Jawa membentuk "new normal" di bawah kolonialisme dengan tetap menjaga nilai-nilai spiritual mereka. Analogi ini relevan dengan kondisi global saat ini, ketika bangsa-bangsa harus beradaptasi dengan sistem global yang menekan namun tetap berusaha mempertahankan identitas moral dan budaya.
Lebih jauh, konsep tahannuts (Robingun & Nugroho, 2024) memberikan inspirasi bagi pendidikan kontemporer: pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan moral dan kesadaran batin. Dalam konteks pendidikan karakter bangsa, Diponegoro dapat dijadikan model pemimpin yang membangun keseimbangan antara intelektualitas, moralitas, dan spiritualitas.
Babad Diponegoro adalah teks yang menyatukan sejarah, spiritualitas, dan budaya dalam satu narasi yang utuh. Melalui babad ini, Pangeran Diponegoro tampil sebagai figur sufi-pejuang yang menggabungkan kesalehan religius dengan perlawanan sosial. Ia tidak hanya melawan penjajahan politik, tetapi juga melawan penjajahan batin — keserakahan, ketamakan, dan kehilangan iman.
Perjuangannya menunjukkan bahwa nasionalisme sejati harus berakar pada spiritualitas dan moralitas. Babad Diponegoro menjadi cermin bagi bangsa Indonesia untuk memahami bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada senjata atau kekuasaan, melainkan pada integritas jiwa. Dengan membaca ulang babad ini, kita tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menemukan fondasi etis untuk masa depan bangsa.
Bacaan;
Achmad, S. W. (2020). Babad Diponegoro. Yogyakarta: Araska.
Carey, P. (2017). Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785–1855). Jakarta: Komunitas Bambu.
Geertz, C. (1976). The Religion of Java. Chicago: University of Chicago Press.
Ibdalsyah, M., et al. (2025). Prince Diponegoro's Islamic Da'wah: Islamization and Jihad from Selarong Cave to the Java War in Yogyakarta. Journal of Posthumanism Studies, 3(2).
Ittihadiyah, H. (2024). A New Normal in the Past: Learn from Historical Events in Bagelen After the Java War (1825–1830). Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities, 8(1), 1–15.
Lombard, D. (1996). Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II – Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia.
Ricklefs, M. C. (2001). A History of Modern Indonesia since c.1200 (3rd ed.). Stanford: Stanford University Press.
Robingun, S. E., & Nugroho, M. Y. A. (2024). Konteks Pendidikan Islam dalam Dimensi Tahannuts Pertemuan Pangeran Diponegoro dengan Sunan Kalijaga. MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, 5(1).
Shofiyulloh, A. (2024). Gerakan Ratu Adil dan Cita-Cita Kerajaan Islam Pangeran Diponegoro di Tanah Jawa 1823–1855. UIN Sunan Kalijaga.
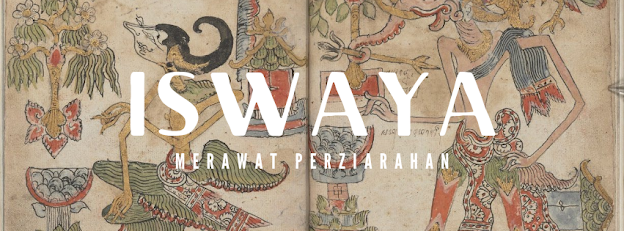
Komentar
Posting Komentar